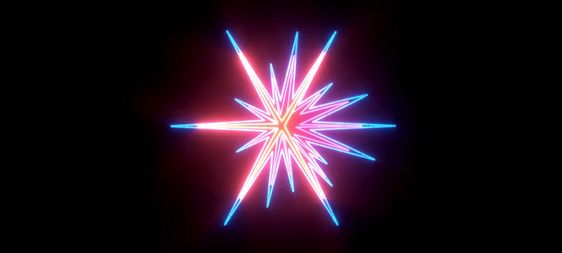Malam itu, aku melihat Ibu begitu bahagia. Senyum manis mengembang sempurna dari bibir yang tersapu lipstik warna merah. Meski aku yakin tubuhnya lelah, tapi Ibu tidak ingin menunjukkan.
Sebulan sebelumnya, seorang prajurit angkatan udara datang melamar Mbak Roisah. Itulah alasan Ibu tidak ingin menyurutkan senyumnya. Malam itu malam pernikahan putri pertamanya.
Saat Ibu bercakap dengan Bulik Lastri–adik almarhum ayah–aku mendengarnya mengatakan, “Alhamdulillah satu anak sudah mentas, Las. Dia telah memiliki jalan kehidupannya sendiri. Masmu pasti bahagia melihatnya.”
Aku jadi ingat, Ibu pernah menasihatiku dengan memakai analogi burung merpati. Katanya induk burung merpati melakukan segalanya demi anak merpati, meskipun itu makanan yang telah masuk ke dalam paruhnya.
Ah, Ibu. Aku paling suka mendengarnya bercerita.
Setahun setelah pernikahan Mbak Roisah, Ibu kembali menggelar pesta. Kali ini untuk Kak Halimah. Setelah menikah, Kak Halimah dan suaminya pun memilih tetap tinggal bersama kami.
Beda dengan Mbak Roisah yang menurutku baik. Aku dan Kak Halimah tidak pernah cocok. Aku tidak suka padanya. Dia sering mengejekku, mengatakan aku anak perempuan, hanya karena kulitku bersih dan terlihat lebih putih dibanding empat saudaraku yang lain.
Dia juga kasar. Dulu sekali, saat ibu menyuruhnya mencebokiku, dia tidak pernah mau memakai tangan kirinya, tetapi selalu menggunakan kaki. Dia bakal marah kalau aku menangis ketika kukunya mengenai kulitku. Menyebalkan!
Bukan hanya itu, Kak Halimah tahu aku takut gelap, tetapi sepertinya sengaja membuatku semakin takut. Saat aku ke kamar mandi, dia sering iseng mematikan lampu. Meski aku telah berteriak, tetap tidak mau menyalakannya lagi. Yang paling membuatku sebal, dia selalu menang dariku.
Pernah suatu hari, saat Ibu tidak di rumah, Kak Halimah mendorongku masuk ke gudang. Aku berusaha mendorong pintu yang hampir ditutup olehnya, tapi lagi-lagi aku kalah. Dia sengaja mengunciku di sana sampai malam. Andai Mas Ardi tidak mengadu, mungkin aku akan mati di sana karena gudang itu jarang sekali dibuka.
Kejadian serupa berulang bahkan setelah dia menikah. Puncaknya sebulan setelah aku dikhitan. Waktu itu aku marah karena mertua Kak Halimah menuduh Ibu menyuruh putrinya menguras harta mereka, katanya demi mencukupi hidup kami yang memang tengah mengalami kesulitan ekonomi.
Aku mendatangi rumah mertua Kak Halimah. Saat itu aku merasa telah dewasa dan berkewajiban membela Ibu. Sial! Rupanya Kak Halimah mengetahui kenekatanku. Menjelang magrib, dia pun memuntahkan semua kemarahannya.
Dia berbuat kasar. Aku berlari. Niatku ingin kabur lewat pintu dapur, apesnya malah lari ke kamar mandi. Seolah mendapat kesempatan, Kak Halimah segera menarik selendang Ibu yang teronggok di kursi. Dia menangkapku. Memaksaku duduk. Mengikat tanganku di balik punggung. Secepat dia menarikku, secepat itu pula dia menyambar serbet untuk menyumpal mulutku.
Hanya dalam hitungan detik Kak Halimah berhasil menyeretku ke kamar mandi. Dia menyiram tubuhku dengan bergayung-gayung air hingga membuatku sulit bernapas. Tubuhku menggigil. Pandanganku mulai kabur. Aku hanya melihat bayangan Kak Halimah keluar dari kamar mandi lalu terdengar bunyi pintu terkunci. Setelahnya aku tak ingat apa-apa.
Saat sadar aku sudah di dalam kamar. Ibu memelukku dan mengusap lenganku. Lirih suaranya meminta kami berempat mendengarkan rahasia besar yang telah lama tersimpan.
Tersedu aku memeluk Ibu. Dia segalanya bagiku. Ibulah merpati yang siap berkorban untuk anak merpati lain. Dialah harimau yang siap melindungi anak harimau lain. Kelima anak Ibu tidak ada yang sedarah, tapi setelah kejadian itu kami berusaha lebih dekat laiknya saudara kandung.